Malam itu kami memutuskan untuk membicarakan banyak hal. Rasanya rumah ini memang tidak akan pernah ada habisnya untuk dibicarakan.
Dari dulu setiap kali kami berkumpul seperti ini, pasti ujung-ujungnya kami akan melakukan perjalanan untuk kabur ke kota lain. Entah hanya sekedar makan jagung bakar, mengunjungi kakak-kakak yang sedang kkn, atau hanya ingin pergi piknik saja sejauh-jauhnya karena rumah itu sedang tidak menyenangkan. Lalu kami pulang dengan dimarai habis-habisan.
Namun kali ini kami memutuskan untuk hanya berkeliling kota, duduk di warkop selayaknya anak muda jaman now yang menghabiskan banyak waktunya untuk “sitting, talking, generally doing nothing” seperti kata NY Times. Lalu kami berpindah ke tepi pelabuhan yang ternyata tetap ramai dengan penjual sari laut walau waktu sudah menunjukkan jam yang seharusnya dinikmati di atas tempat tidur dengan rindu atau betul-betul tidur.
Tapi kami tidak bersepakat untuk menganggap nongkrong seperti ini adalah kegiatan membuang-buang waktu. Karena semalaman kami berbicara tentang rumah yang sama-sama ditempati, berdiskusi tentang filsafat dan politik, mimpi, pilihan-pilihan, dan pada akhir kami berbicara tentang diri kami masing-masing. Walaupun kami telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Kami sadar telah banyak berubah. Tapi kami tetap tahu teman yang duduk bercerita di depan sekarang adalah sama dengan teman yang disapa saat pertama kali memasuki kampus dengan seragam hitam putihnya. Riuh ya?
Bagi saya, cinta itu seperti ini. Ah, bisa-bisanya dengan sepede itu saya mengatakan ini cinta. Tapi apa yang diajarkan oleh rumah itu membawa kontribusi besar kepada diri kami di hari ini. Bahkan kepada hubungan kami satu sama lain. Lalu saya pernah bertanya kepada seorang teman, “kenapako masih mau tinggal? banyak sekaliji hal yang mungkin lebih baik di luar sana daripada di sini”. Dia hanya menjawab, “Saya tidak tau jawaban seperti apa yang kau mau. Tapi mungkin karena cinta” yang juga jawaban saya atas pertanyaan yang setiap hari saya tanyakan kepada diri sendiri itu.
Malam itu saat perjalanan pulang, kami berlima bersama jalanan yang kami harap mungkin bisa selapang itu setiap hari juga lampu-lampu kota yang begitu puitis, memutuskan untuk diam dan menikmati suara Rara Sekar dan Ananda Badudu yang seperti mewakili pertanyaan dalam hati “Badai Tuan telah berlalu, salahkah ku menuntut mesra?”. Tempo yang lambat membuat kami berdiskusi kecil lagi bahwa hidup memang tidak perlu harus terburu-buru. Nikmati saja. Santelah, ucap teman saya.
Tapi setelah suara Rara Sekar dan Ananda Badudu kembali menautkan “Selamanya sampai kita tua. Sampai jadi debu” kami terdiam kembali. Mungkin sibuk memaknai apa sebenarnya yang dimaksud folk duo yang baru-barusan bubar ini atau mungkin kami sedang berharap di hati masing-masing untuk bisa menjadi seperti makna di judul lagu ini.
Sampai jadi debu.
Makassar, 20 Maret 2018

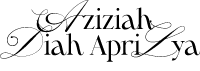

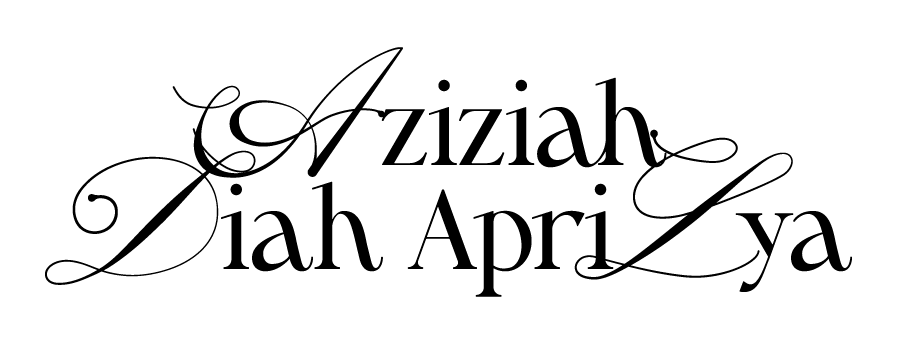

Comments
Indah Pakpahan
Aziziah Diah Aprilya