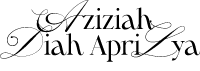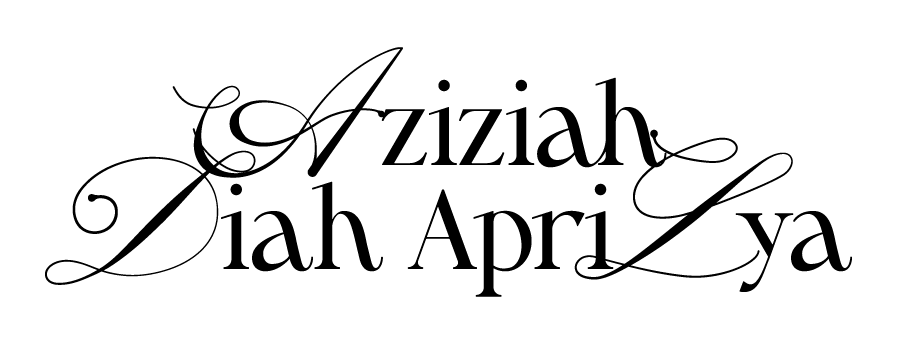Bersih dan kosong. Kesan pertama saya ketika memasuki rumah nenek lagi. Sepertinya sudah sepuluh tahun lalu semenjak terakhir saya ke kampung bapak di Padang-Padang, sebuah dusun di Desa Kurrusumanga. Dulu setiap kali mamaku mengatakan kita akan ke Kabupaten Luwu ini, saya akan merengut. Saya membayangkan betapa mualnya perjalanan delapan jam dari Makassar ke sana. Juga perasaan-perasaan asing karena setiap orang lebih sering berbicara dengan Bahasa Bugis yang tidak saya mengerti. Tapi kali ini saya kembali ke rumah nenek tanpa keluarga. Saya datang bersama Wilda, teman peneliti dan Pak Naufal, seorang supir.
Saya memasuki rumah yang sudah lapang itu. Tidak ada perabotan. Hanya ada karpet besar di tengah ruangan. Saya berjalan memeriksa setiap kamar. Berusaha mengingat dimana kamar nenek. “Kau ndak takutji toh di sini?” tanya Om Aris, adik dari bapak. Ia yang kini memegang kunci rumah ini. Saya mengangguk yakin walau sebenarnya ada sedikit rasa takut. Semenjak nenek meninggal beberapa tahun yang lalu, rumah ini sudah jarang dihuni. Hanya beberapa kali ketika mama dan bapakku datang berkunjung. Tapi entah kenapa, bau rumah ini membuat saya nyaman. Bau yang sama seperti ketika semua perabotan masih ada dan nenek masih hidup.
Kami kemudian menaruh barang-barang di kamar. Setelah omku dan supir pergi, saya berjalan ke kamar mandi. Saya sadar betapa kecilnya WC ini sampai dulu kami harus menaruh peralatan mandi di pinggir bak. Hal yang membuat tangan saya sering tidak sengaja menyenggol sampo, sabun, atau sikat gigi masuk ke dalam bak. Dulu waktu kecil, saya bisa panik karena lengan pendekku tidak mampu menjangkau sampai ke dasarnya. Kini walau tanganku sudah bisa menggapai dasarnya, saya masih tetap menjatuhkan sesuatu ke sana.
Setelah membersihkan diri, lampu kamar dimatikan. Saya berbaring bersama Wilda. Bayangan teralis jendela kemudian terlihat di tembok karena cahaya lampu jalan menjatuhkannya. Bayangan itu tepat berada di depanku. Sesekali terlintas pikiran gila akan siluet hantu yang mungkin tiba-tiba muncul di tengah sana. Tapi saya memilih memejamkan mata saja. Tentu saya tidak bisa langsung tertidur. Hingga jam menunjukkan pukul dua lewat, kepala saya mulai ringan dan saya akhirnya terlelap.
Langit masih gelap ketika Wilda menyuruh saya bangun. Kami memang sudah bersepakat untuk bangun lebih pagi karena pasar yang ingin kami kunjungi ada di Kota Palopo. Sekitar 50an Km dari Kecamatan Belopa ini. Setelah terseok-seok bersiap, saya dan Wilda akhirnya dijemput supir untuk segera menuju ke arah Utara Tana Luwu1 ini.
Kami melewati masjid, sawah, dan rumah-rumah. Berbagai memori saya juga ikut melintas di sepanjang jalan desa ini. Salah satu yang paling berkesan tentu saat pertama kalinya saya berjumpa dengan kunang-kunang. Saya masih bisa merasakan buncahan hati ketika itu. Saya, mama, dan sepupuku sedang berjalan pulang dari salat tarawih di masjid ketika kunang-kunang terbang ke arah kami–seperti sengaja menghampiri untuk memberi salam. Saya, anak kecil yang besar di Kota Makassar tentu kegirangan. Selama ini kunang-kunang hanya bisa saya lihat di televisi. Tapi kini serangga itu berpendar di dekatku. Sepupuku hanya tertawa melihat kehebohan itu. “Begitu memang anak kota” sindir mamaku saat itu.
Setelah satu jam berkendara, kami akhirnya tiba di depan Kantor Walikota Palopo. Kami menjemput Kak Zulham, pegawai negeri yang juga senang meneliti dan mengarsip. Ia yang akan menemani kami selama penelitian tentang pengasam (pacukka) di Palopo. Lelaki itu kemudian mengajak kami ke Pasar Rakyat Andi Tadda. Lokasi yang wajib kami kunjungi. Setiap saya dan Wilda tiba di kabupaten atau kota yang menjadi tempat penelitian pacukka, hal pertama yang kami lakukan ialah mengunjungi pasar lokal. Pada pasar lokal lah kita bisa menavigasi seberapa banyak panen panganan tertentu, juga asal berbagai bahan itu ditanam. Jadi sesampai di pasar, kami langsung berkeliling di lorong-lorongnya.
Kami selalu mendapati patikala, pengasam yang kami cari di meja-meja pedagang. Hanya saja kebanyakan dari patikala itu tidak sesegar yang kami kira. Bahkan ada beberapa yang sudah membusuk. Pada satu pedagang yang masih memiliki patikala segar, saya meraih satu kuncup kecombrang yang terlihat seperti tulip. Bau asam yang khas seketika tercium.

Setelah dari Pasar Andi Tadda, kami lalu mengunjungi Pasar Sentral Palopo. Berkeliling melihat penjual patikala yang kondisinya tidak begitu jauh berbeda dengan pasar sebelumnya. Kami kemudian memilih untuk melihat pelelangan ikan di pesisir Palopo yang tidak jauh dari sana.
Mobil kami bergerak dan di sebelah kiri pegunungan terhampar jelas. Berlatarkan gunung, para nelayan tampak sudah berdiri di depan dagangan ikan-ikan tangkapan mereka. Berteriak dengan berbagai nama ikan yang mereka punya. Tentu kamera mirrorless yang kukalungkan membuat beberapa orang memanggil untuk ingin difoto. Saya kadang langsung memotretnya, tapi lebih sering mengabaikan panggilan itu karena takut para pembeli lain terganggu, apalagi kondisi pelelangan pagi itu cukup padat.
Saya berjalan ke ujung dermaga, memperhatikan lanskap pegunungan yang berdampingan dengan laut ini. Saya memotretnya. Tapi setiap kali hasil foto itu saya lihat, saya merasa ia biasa saja. Tidak ada yang bisa menggantikan keindahan pemandangan itu dengan tampakan langsungnya. Apakah karena sebuah foto tidak bisa merekam bau amis ikan yang bercampur dengan bau mentega dari jajanan pukis di sana? Mungkin foto juga tidak bisa membuat kita mendengar suara megafon penjual obat dengan narasinya yang penuh keajaiban? Ia barangkali terlihat indah karena seluruh indra saya merasakannya dengan utuh.

Beranjak dari sana, kami naik ke Kambo, sebuah kelurahan yang berada di dataran tinggi Palopo. Semakin kami naik, semakin warna merah mencuat di samping kanan dan kiri jalan. Ternyata patikala ada dimana-mana di tempat ini. Kak Zulham lalu singgah di rumah seorang warga yang ia kenal. Namanya Hapsa. Neneknya memiliki kebun patikala di samping rumahnya. Kami lalu diajak untuk berkeliling kebunnya. “Agak berantakanki ini karena nenek lagi sakit, jadi ndak bisaki turun urus kebun” ucap perempuan berumur 26 tahun itu. Seorang lelaki kemudian datang menghampiri kami. Ia adalah keluarga Hapsa yang juga mengurusi kebun Patikala.
“Dulu waktu kecil, kita suka cemili ini daunnya kecombrang karena maniski” kata lelaki yang bernama Dandi itu. Ia lalu menjelaskan kalau buah patikala hanya tumbuh di tunas yang muda. Setelah tua, batang patikala akan memanjang tiga hingga empat meter dan kemudian berhenti berbuah. Tapi proses itu diiringi dengan tumbuhnya tunas-tunas kecil di sekelilingnya. Saya seketika mengingat konser Iwan Fals di awal tahun 2020 di Makassar. Saat penonton mulai beranjak pulang, tiba-tiba suara gitar Iwan Fals kembali terdengar.
“Satu satu daun berguguran
jatuh ke bumi dimakan usia”
Saat itu, saya pelan-pelan melangkah untuk mendengar lebih jelas. Lagu itu asing. Bukan lagu Iwan Fals yang biasa saya dengarkan. Tapi suaranya begitu teduh dan lirik yang samar-samar itu saya coba cermati.
“Satu satu tunas muda bersemi
Mengisi hidup gantikan yang tua
Tak terdengar tangis tak terdengar tawa
Redalah reda”
Beberapa penonton yang terlihat lebih tua berhenti dan kembali bernyanyi bersamanya. Beberapa yang muda berlalu begitu saja. Mungkin mereka juga seperti saya yang tidak akrab dengan lagu ini. Tapi dengan tubuh yang sudah kedinginan akibat hujan di tengah konser, saya tetap tinggal. Lagu berjudul “Satu Satu” itu terlalu indah untuk dilewatkan. Sampai akhirnya konser berhenti, Namun lagu yang dirilis tahun 1994 itu terus hidup di daftar putar saya. Liriknya mengingatkan saya akan patikala-patikala ini. Juga akan sebuah siklus hidup yang saya saksikan dimana-mana.

“Jarang ada anak muda yang mau bertani di sini” kata Dandi. Ia dan Hapsa juga bagian dari orang-orang muda Kambo. Mereka baru saja lulus kuliah dan sedang sibuk mengurus Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata). Komunitas yang mengerjakan festival, lokakarya, konten sosial media, dan pendokumentasian untuk Kambo. Saya dan Wilda tentu langsung mengajak mereka untuk menjadi tim asisten lokal untuk penelitian kami.
Selama berkeliling untuk mengobservasi lokasi dan cerita pacukka ini, kami selalu mendapati berbagai orang muda yang setia menemani kami di setiap wilayah. Mulai dari Pinrang, Enrekang, dan kini Palopo. Saya tersentuh mengetahui bagaimana mereka memahami setiap tumbuhan pengasam ini seperti seorang saudara. Bukan hanya sekedar bumbu masakan, tapi juga sesuatu yang hidup dan tumbuh bersama. Mereka membuat pengasam bukan hanya menjadi pembawa rasa yang khas di makanan orang Sulawesi, tapi juga media penyampai kisah dan harapan di dalam tempatnya hidup.
“Setiap saatji ini ada patikala. Mau hujan, mau kemarau, ada terusji di sini” Kata Hapsa saat kami menanyakan kapan warga memanen patikala.
Kak Zulham lalu membawa kami menemui seorang pembuat sirup patikala. Ia dipanggil Mama Syifa. Wajahnya terlihat begitu lelah saat kami berkunjung ke cafenya. Tapi ia masih ingin meladeni pertanyaan-pertanyaan kami tentang sirup patikalanya.
“Sebenarnya waktu itu kami dikasih tantangan. Bagaimana caranya mengolah patikala selain untuk Parede atau Kapurung” Ujar Mama Syifa sambil membuatkan kami Patikala Squash, minuman racikan sirup patikala, soda, lemon, gula, dan es batu. Ia mendapatkan resep itu dari pelatihan Politeknik Pariwisata di tahun 2023. Kami lalu mencicipi minuman itu. Rasa asam dan sodanya begitu menyegarkan di tengah terik matahari Palopo.

Setelah pamit dan berjanji akan kembali, kami turun kembali ke kota. Saya kemudian mengajak Wilda dan Kak Zulham untuk mengunjungi rumah adik dari kakekku. Saya memanggil beliau dengan Nenek Batara karena rumahnya ada di Jalan Batara. Saat kami sampai dan masuk ke halamannya, ia tampak kebingungan karena saya memang sudah sangat lama tidak berkunjung ke sana. Tapi beberapa saat kemudian ia langsung menyadari. Akhirnya ia memeluk saya. Tiba-tiba saya merasa begitu hangat.
Nenek Batara ialah tante bapakku. Ia yang membesarkan bapak. Mulai dari bapak masih di Sekolah Dasar hingga ia SMA. Bahkan wisuda bapak dihadiri olehnya, bukan oleh mama kandungnya. Saya mengetahui itu saat melihat foto wisuda bapak menggantung di rumahnya.
“Bapakmu dulu itu pintar sekali. Ranking satu terus. Makanya dia lolos tes di Unhas (Universitas Hasanuddin). Siapami naturunkan itu semua?” Tanyanya. “Saya lah” Jawabku santai. Ia dan anak-anaknya tertawa.
Dari dulu saya senang melihat Nenek Batara. Ia murah senyum dan sangat cantik. Saya selalu merasa ia mirip dengan Audrey Hepburn. Ingatannya juga masih begitu baik. Walau ia tidak tahu berapa umurnya. Penanda yang ia ingat hanyalah ketika kelas 1 SR (Sekolah Rakyat), ia melihat bapaknya dipukuli oleh tentara Belanda. Selain itu, ia juga mengingat tentang bagaimana buyutku dan kakeku belajar tarekat di waktu-waktu itu.
“Kakekmu itu karmanya baik” ucapnya. Sayangnya, saya hanya mengenal Kakek Nurdin dari cerita-cerita. Beliau meninggal jauh sebelum saya lahir. Tapi saya tetap senang karena segala cerita yang mereka ucapkan hanyalah tentang kebaikannya.
Saya kembali menatap dinding-dinding rumah Nenek Batara yang penuh dengan berbagai foto. Mulai dari foto bapak, anak-anak kandung nenek, cucu, bapaknya, para pemimpin tarekat, juga fotonya sendiri. Semua dipajang melingkari ruang tamu, seakan memeluk rumah itu. Berbekal foto-foto itu lah, segala cerita saya pertanyakan dan simak kembali. Dulu saya hanya mendengarnya sepotong-sepotong karena diri saya yang masih kecil lebih senang bermain dan makan. Kini rasanya semua cerita seketika menjadi sesuatu yang penting. Barangkali saya akhirnya sadar kalau hanya memori-memori ini yang membuat segala yang pergi tetap ada.
Nenek menatapku dan memelukku lagi. Tinggal jauh di Makassar, membuatku tidak begitu punya interaksi yang dalam dengan kakek dan nenek kandungku. Mereka tinggal di kota lain yang harus ditempuh dengan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Saya selalu merasa berjarak dengan mereka. Baik secara fisik maupun mental. Tapi sore itu, pelukan Nenek Batara mengembalikan perasaan yang saya kira selalu jauh itu. “Ke sinika lagi nanti nah?” Tanyaku. Ia hanya mengatakan, “Langsung meki saja ke sini. Kah rumahta ji” Jawabnya sambil tertawa.
Ada sebuah ucapan yang sering dipakai di Sulawesi Selatan untuk mendoakan seseorang. Kurruq Sumangeq. Sebuah harapan agar semangat (jiwa) selalu ada di dalam tubuh orang yang didoakan. Kak Jimpe, kawan di Kampung Buku pernah menjelaskan ucapan itu dengan “memanggil sesuatu untuk kembali ke tempatnya” karena sumangeq seperti sebuah energi yang bisa saja redup, bahkan hilang, tapi ia tidak akan pernah mati. Bagi Louie Buana, teman saya yang mendalami manuskrip La Galigo, ia mengibaratkan ucapan itu seperti seekor burung. Ketika doa dirapalkan, sang burung kembali menuju sarangnya. Ia terbang ke hati.
Saya mengingat itu semua sembari beranjak pulang ke Desa Kurrusumanga.