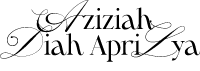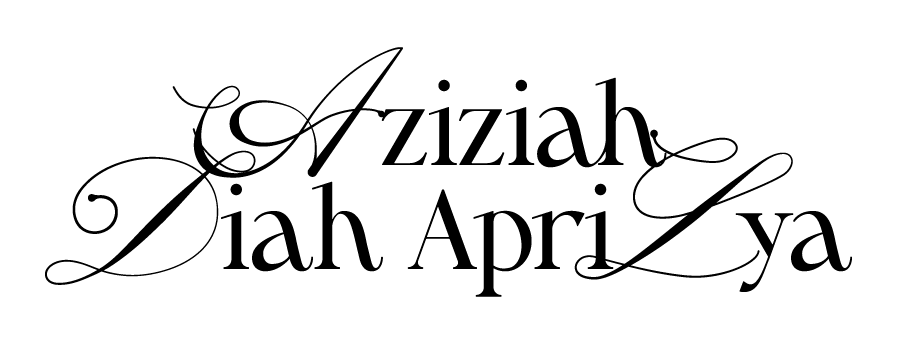Wiji Thukul mungkin tidak akan pernah menyangka hanya dari puisi-puisi sederhananya yang jujur itu telah lahir sebuah film panjang yang telah pergi ke banyak festival.
Dan sampai sekarang tetap diputar juga didiskusikan di berbagai kota.
Mungkin dari puisi sependek “kemerdekaan itu nasi, dimakan jadi tai” dia tidak akan menyangka bahwa itu telah menghiasi berbagai sosial media orang-orang, entah karena mereka menganggap itu adalah suara ketidakadilan yang coba Wiji Thukul sebarkan agar semua orang dari berbagai lapisan ekonomi ini bisa mengerti atau hanya karena orang-orang menganggap kalimat itu “lucu” dan tidak peduli apa konteks saat Wiji mengatakan itu.
Tapi itu bukan salah siapa-siapa. Saat seseorang telah berkarya dan dia menyebarkan karya itu, saat itu juga dia telah “mati”. Orang-orang bebas melakukan apa saja dengan karya itu, mau mereka “hidupkan” dengan tulisan penuh caci, puisi penuh kekaguman, foto, film, atau apapun itu bahkan hanya dengan lontaran ucapan yang tidak logis, pengarang telah “mati”.
Bagi saya itulah menariknya sebuah karya. Entah dalam medium apapun itu.
Jadi ketika teman-teman saya meminta sebuah puisi untuk festival yang diadakan oleh teman sefakultas, saya sangat senang. Akhirnya tulisan ini melahirkan anaknya.
Bukannya ingin menyandingkan diri dengan Wiji Thukul, saya hanya tiba-tiba tersadar bahwa sebuah karya mungkin akan sangat menyenangkan jika bisa lahir kembali dengan karya lain. Apalagi jika dia hidup dalam sebuah gerak yang dapat kita lihat dan dengar.
Puisi saya jika hanya berakhir di note HP dan saya nikmati sendiri rasanya cukup menyedihkan. Saya tidak ingin mengurung sesuatu yang mungkin lebih baik hidup dengan merdeka. Kata-kata itu akhirnya saya lepas untuk terbang ke dahan manapun yang dia inginkan.
Hari ini puisi itu hidup kembali pada teman saya yang membawakannya dalam teaterikal dan diiringi oleh lagu Manusia Setengah Dewa-nya Iwan Fals. Ketika melihat puisi itu dialunkan rasanya kata-kata yang telah saya tulis itu terlepas dari saya dan mencoba berbicara kepada saya sebagai sesuatu yang berbeda. Saya tidak melihatnya lagi sebagai milik saya saja, tapi kata-kata itu telah sepenuhnya hidup di gerak dan suara oleh mereka yang membawakan.
Dan saya bahagia setelah kata-kata itu beristirahat di gadget ini, akhirnya dia terbang dan menjalani kehidupan yang lebih baik.
_
Puisi itu hanya menceritakan bagaimana pendapat saya soal kota. Saya tidak mau mengajak siapapun untuk bersepakat. Saya senang kalau ada yang bisa membalasnya atau meminjamnya untuk lahir kembali menjadi karya yang lain. Toh kita semua juga sedang melakukan imitasi-imitasi tanpa kita sadari. Tulisan saya tidak mungkin bisa lahir tanpa pengaruh dari penulis lain. Saya hanya meminjam bagian dari mereka yang saya sukai lalu saya terapkan sendiri.
Menyoal tentang puisi saya itu lagi, entahlah. Saya senang ketika selesai menulisnya karena itulah yang saya pikirkan soal kota ini. Lalu teman-teman saya meminta puisi itu untuk dibacakan dan berlipatlah rasa senang itu karena mereka membawakannya dengan merdeka, jujur, dan apa adanya.
Karena saya orang yang tidak mungkin berdiri membacakan puisi dengan cara seindah itu. Jadi saya sangat berterimakasih kepada teman-teman yang telah membawanya untuk didengarkan dan melakonkannya dengan sangat menyenangkan.
Kata-kata itu tanpa kalian mungkin tidak akan hidup dengan cara seindah ini.
Semoga nanti dia bisa hidup berbeda lagi di lain tempat.
_
Bolehlah saya simpan puisi sederhana itu di sini.
Sedihnya saya tidak punya judul untuknya.
Kemarin dinding-dinding beton itu menangis kepada langit
Mereka bilang sudah tidak ingin berdiri menopang orang-orang egois ini
Mereka meminta kepada langit untuk menurunkan hujan selamanya
Biarkan saja banjir
Agar ada yang sadar
Bahwa pijakan yang mereka aspal itu tidak menyerap air hujan
Tapi malah hanya mendatangkan air mata
Di bawah sana seorang mahasiswa yang buta dan tuli terus duduk di halte kota
Memeluk buku yang tidak akan dia baca
Mendengar tangisan ketidakadilan yang tidak akan pernah dia dengar
Tapi dia tersenyum bahagia
mengira kota ini begitu indah
terlupa kalau kota itu penuh nestapa
Bintang-bintang yang cemburu pada lampu-lampu kota akhirnya pergi dari malam.
Seberapa keras usaha cahaya alam itu,
Tidak akan mampu mendapatkan indahnya di tengah kabut polusi.
Tapi mau pergi sejauh apapun,
Cahaya itu akan selalu Ada
Cahaya itu telah menyatu bersama malam.
Mungkin menunggu untuk ditemukan
oleh siapapun yang bersedia.
Kota yang diselimuti awan abu-abu itu
akan menemukan matahari terbit esok paginya.
Pilihan siapa saja untuk tertidur atau menyambutnya..
Saya tidak tahu kenapa saya ingin mengatakan ini. Tapi saya hanya ingin bilang kalau kata-kata tidak berarti apa-apa, pastilah Wiji Thukul tidak akan menjadi buron hanya karena telah menulis puisi.
Makassar, 19 April 2018