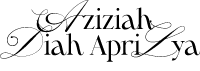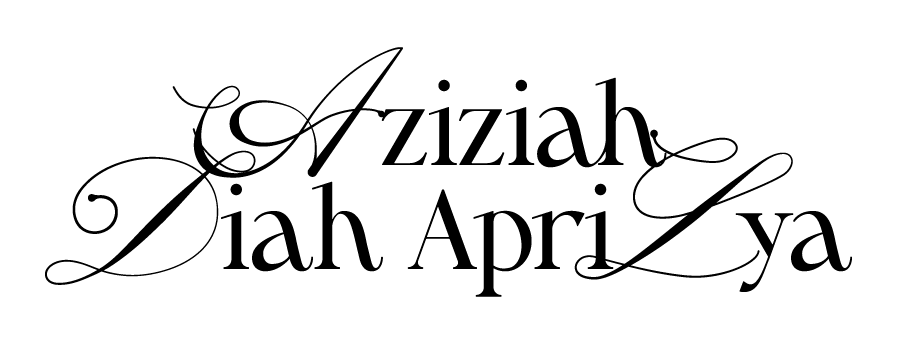Setiap kali ingin memulai menulis di sini, rasanya seperti akan memberi orang lain kesempatan untuk melihat hal-hal yang sebenarnya hanya ingin saya nikmati sendirian. Namun di saat yang sama, mengetahui bahwa barangkali tulisan ini akan berpindah menjadi ingatan atau kenangan untuk orang lain membuat saya merasa tidak sendiri. Dan entah kenapa itu menjadi jauh lebih penting.
Setelah puncak ketakutan pandemi di sepanjang 2020, tahun 2021 saya mulai melakukan beberapa perjalanan lagi. Jika harus jujur, saya tidak pernah betul-betul niat untuk keluar rumah. Saya suka sekali dengan kamar saya. Ada banyak tumpukan buku, film, album yang tidak apa-apa jika harus saya habiskan sendirian di dalam kamar. Namun fotografi, sesuatu yang mulai saya pakai untuk mencari uang selalu menyeret saya keluar dari pintu rumah, bahkan pergi dari pulau Sulawesi.
Setelah ditolak pesawat dua kali karena kuota penumpang yang tidak terpenuhi, saya terbang ke Surabaya untuk melakukan perjalanan darat selama beberapa jam ke Kabupaten Bojonegoro. Nama tempat yang begitu asing. Bojo? Pasangan? Negoro? Negara? Negara Pasangan, lelucon yang saya temukan bersama supir waktu itu.

Di tempat yang suhunya bisa sampai 39 derajat itu, saya ikut dalam sebuah produksi film berjudul Autobiography. Ceritanya tentang anak asisten rumah tangga yang harus mengurusi kampanye majikannya yang seorang pensiunan jendral. Saya ingat betapa malasnya saya sewaktu diminta untuk membaca skenarionya, tapi beberapa saat ketika dua halaman sudah terlalui, tanpa sadar saya sudah berada di lembar 100an yang dekat sekali dengan halaman terakhir. Impresi yang sama ketika saya menikmati Laut Bercerita-nya Leila S. Chudori, puisi-puisi Wiji Thukul atau tulisan-tulisan Benedict Anderson. Menemukan kembali penggalan, catatan dan warisan masa 32 tahun yang berakhir tepat saat saya berusia satu tahun.

Selain saya senang menjadi bagian dari film itu, mendokumentasikan orang-orang di balik layar membuat saya juga kembali bertemu dengan manusia yang banyak dan baru lagi. Seperti biasa saya bukan tipe manusia yang hobi basa-basi. Namun membuat orang nyaman berada di depan lensa kamera adalah etika yang perlu saya jaga. Semua orang layak berbahagia di depan kamera dan untuk prinsip itu, saya perlu akrab dengan mereka.
Rasanya tentu tertatih-tatih. Di satu waktu sarapan, Wojciech Staron, sinematografer untuk film ini menceritakan pengalamannya saat mengerjakan dokumenter di Argentina. Baginya orang-orang di sana begitu baik dan saya lalu menimpalinya, “the world isn’t a bad place” walaupun sebenarnya saya juga hanya sedang berusaha meyakini pernyataan itu.
“Yup. If you believe it’s bad, it’s bad” tambahnya.
Saya mengingat seorang penulis dari Brazil yang begitu populer dengan satu kalimatnya, “When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it”. Kata-kata itu begitu saya senangi di masa-masa awal kuliah, saat saya pertama kali membaca bukunya yang berjudul The Alchemist, cerita Santiago yang berkelana mencari harta karun hanya dengan berbekal mimpi dan tafsiran seorang peramal. Kalimat itu kalau tidak salah diucapkan oleh seorang raja yang tidak sengaja bertemu Santiago saat ia ragu ingin mepercayai mimpinya itu. Bagian kesukaan saya adalah ketika kalimat yang sering tersebar di media sosial itu berubah bentuk menjadi gombalan Santiago ketika bertemu seorang wanita di salah satu tempat transitnya, “So, I love you because the entire universe conspired to help me find you” seperti perpaduan antara takdir dan pilihan.
Tahun ini pula saya merasakan hal-hal yang pasti, takdir–kalau boleh kita katakan begitu adalah konsekuensi dari pilihan-pilihan. Seperti saya tidak pernah mengira akan lulus kuliah di awal tahun, tapi karena harus mengejar wisuda untuk ikut produksi film, saya terpaksa menyelesaikan skripsi. Seperti juga memutuskan untuk tidak memilih bekerja di kantor setelah wisuda, karena sepertinya diri saya yang kacau ini tidak sesuai dengan rutinitas waktunya yang ritmis itu. Walau saya harus berhadapan dengan anggapan sebagian orang bahwa tidak bekerja di kantor adalah sama saja dengan pengangguran, tidak melakukan apa-apa. Di luar saya yang tidak sepakat dengan konsep itu, memang kenapa kalau seseorang tidak melakukan apa-apa dan hanya bermalas-malasan? toh itu barangkali jauh lebih baik dibanding orang yang bekerja di gedung-gedung besar dan mengambil uang rakyat untuk kepentingan pribadinya. Okay, sounds too grumpy here.

Dalam prolog Siapa yang Memasak Makan Malam Adam Smith yang ditulis Katrine Marcal, jurnalis asal Swedia, ia tidak sepakat dengan awalan kisah feminisme yang selalu berbunyi “Pada 1960an kaum perempuan pergi bekerja”. Baginya, perempuan sudah selalu bekerja. Hal yang terjadi belakangan adalah perempuan berganti pekerjaan. Dari bekerja di rumah, kini ada juga yang di luar rumah. Sesederhana itu.
Saya ingat saya paling keberatan kalau mama saya yang menghabiskan seluruh waktunya selama ini sebagai ibu rumah tangga—memasak, membersihkan rumah, mencuci, menyetrika baju dan belanja di pasar dianggap tidak bekerja. Bahkan tidak dianggap setara dengan orang-orang yang berseragam, duduk 8 jam di depan komputer dan memiliki penghasilan tetap tiap bulan. Kalau kata Marcal yang bisa lebih jauh lagi menariknya, tidak diperhitungkan sebagai “aktivitas produktif” dalam sistem perekonomian. Padahal kalau ibu dari Adam Smith tidak memasak makan malamnya Smith, mungkin salah satu pelopor kapitalisme itu tidak bisa menulis The Wealth of Nations, pemikirannya yang mempengaruhi ilmu ekonomi dunia.

Di tengah berbagai cerita kawan perempuan saya yang harus menuruti keinginan keluarganya atau orang-orang di dekatnya ketika ingin melakukan sesuatu, saya sadar bisa memilih apa yang betul-betul saya inginkan juga merupakan kemewahan, privelese. Walaupun seringkali pilihan itu juga tidak selalu usai di titik yang betul-betul saya inginkan, tapi untuk punya kesempatan memilih, itu cukup membuat saya bahagia.
Berurusan dengan fotografi juga bagi saya ternyata adalah bagian penting akan kesadaran sebuah pilihan itu. Memilih peristiwa yang akan dipotret artinya memeriksa kembali isi kepala tentang posisi, kepentingan dan konsekuensi akan satu gambar. Kadang pula apa yang saya inginkan itu harus terlewati akibat dari ketidakpekaan atau ia terlalu sekelibat terjadi. Namun entah darimana keyakinan ini hadir–saya percaya bahwa setiap kejadian yang tidak berhasil saya potret akan kembali lagi, mungkin suatu hari nanti. Entah dalam bentuk yang serupa atau berbeda sama sekali. Jadi saya tidak pernah betul-betul kecewa jika sesuatu harus saya biarkan lepas.
Bahkan juga jika ia tidak kembali, saya yakin tetap bisa baik-baik saja.

Saya baru saja menyelesaikan tulisan tentang pengalaman menjadi asisten kurator di Makassar Biennale 2021. Beberapa hari yang lalu saya membacanya ulang. Ada perasaan takjub dengan refleksi saya sendiri, sekaligus ada hal-hal yang.. kenapa saya harus menulis itu lagi? Saya merasa agak berlebihan menyampaikan isi kepala sendiri, seakan ada ide atau konsep yang terasa saya paksakan terhadap tempat tinggal saya yang mungkin belum sesuai untuk itu. Namun di satu sisi, saya merasakan bahwa itu kekurangan yang sepertinya perlu diisi. Atau apakah itu hanya kebenaran bagi saya sendiri?
Di luar dari itu semua, saya tetap senang bisa menulis catatan yang cukup panjang itu dengan hati-hati dan lambat. Saya menikmati setiap kali saya memberikan draf awal tulisan itu kepada orang-orang terdekat dan kami akan berdiskusi panjang lebar setelahnya. Rasanya kata-kata itu bukan milik saya sendiri lagi, tapi kepunyaan banyak sekali orang. Mungkin ia tidak akan merasakan sepi–jika ia punya perasaan.

Kalau tahun 2021 punya warna, mungkin warna itu adalah biru. Biru yang selalu diasosiasikan dengan kesedihan. Namun bagi saya, blue is the warmest color. Biru adalah tanda bahwa langit sedang cerah. Biru pula yang menjadi warna laut yang begitu hangat di pantai Bulukumba sana, satu dari sekian tempat yang membuat saya selalu ingin kembali.
Jika di masa depan nanti ada yang menawarkan mesin waktu, mungkin saya mau memilih tahun 2021 untuk kembali. Bukan untuk mengubah apa-apa, tapi hanya ingin merasakannya satu kali lagi.
Makassar, beberapa hari setelah pergantian tahun.